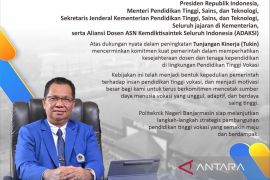Banjarmasin (ANTARA) - Tunjangan Kinerja Dosen ASN, Bagaimana Realita di Lapangan..
Sejak awal tahun 2025 berita terkait protes dosen Indonesia atas pembayaran tunjangan kinerja memenuhi berbagai media online, baik di sosial media maupun di berbagai situs berita.
Para dosen dari berbagai wilayah Indonesia beramai ramai melontarkan kekecewaan dan protes melalui akun sosial media wakil rakyat (DPR dan DPRD) dan juga akun sosial media milik Kementerian Pendidikan Tinggi.
Berbagai berita protes dan artikel opini dari para dosen terkait isu tukin juga bermunculan.
Mengapa isu ini menjadi pusat perhatian para dosen di Indonesia?
Tunjangan kinerja atau disingkat dengan tukin secara umum merupakan bentuk kompensasi atas kinerja pegawai, di mana bentuknya dapat berupa tunjangan finansial maupun non finansial.
Isu tukin menjadi perhatian utama di tahun 2025 ini setelah beberapa bulan sebelumnya, Fatimah, salah satu dosen dari Politeknik negeri Tanah Laut, provinsi Kalimantan Selatan, mencuatkan berbagai kejanggalan yang ditemuinya dalam implementasi peraturan mengenai tukin di Kementerian Pendidikan Tinggi.
Walaupun sesungguhnya masalah tukin dosen ini sendiri sudah berlangsung lebih dari 1 dekade, hanya di tahun 2025 ini suara protes yang dilakukan para dosen ASN menjadi sangat lantang.
Pada tahun 2013, protes serupa pernah disuarakan oleh Abdul Hamid (saat ini beliau telah almarhum), dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, Banten.
Dalam protesnya Abdul Hamid menuntut revisi atas Perpres 88 Tahun 2013, karena di dalam perpres tersebut terdapat pasal yang mengecualikan dosen untuk mendapatkan tukin. Pada tahun 2014, ancaman untuk uji materi perpres 88 tahun 2013 juga pernah dilayangkan oleh Ketua Forum Akademisi Informasi dan Teknologi (FAIT) Hotland Sitorus, yang juga dosen di Universitas Tanjung Pura, Pontianak, Kalimantan Barat.
Pengecualian dosen untuk mendapatkan tukin dalam Perpres 88, 2013 adalah bentuk kecacatan peraturan yang harus diperbaiki.
Akhirnya, pada tahun 2015, Perpres 88, tahun 2013 tersebut resmi dicabut dan digantikan oleh Perpres 151, tahun 2015 di mana didalamnya tidak ada pasal pengecualian dosen ASN dalam mendapatkan hak tukin.
Selanjutnya Perpres 151, 2015 digantikan oleh Perpres 136 tahun 2018.
Pada intinya perpres terakhir yang masih berlaku hingga saat ini tidak pernah mengecualikan dosen dalam perolehan hak tunjangan kinerja.
Secara eksplisit peraturan tersebut memberikan ruang segar bagi dosen ASN Indonesia dalam peningkatkan kesejahteraan mereka melalui sebuah tunjangan finansial.
Sayangnya ruang segar tukin dosen ASN hanyalah berupa angin yang berhembus tanpa realisasi sama sekali.
Jika Kementerian lain yang memiliki formasi dosen ASN dengan segera merespon tunjangan finansial tukin tersebut, tidak demikian dengan Kementerian Pendidikan Tinggi.
Sebagai contoh, Kementerian agama telah merealisasikan tukin bagi dosen ASN nya sejak tahun 2016 melalui Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pemberian, Penambahan, dan Pengurangan Tunjangan Kinerja Pegawai Pada Kementerian Agama.
Demikian halnya dengan Kementerian Pariwisata, sejak berlakunya Perpres Nomor 54 Tahun 2021 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, maka dosen di bawah Kementerian tersebut mendapatkan realisasi hak tukinnya.
Dari sini dapat kita lihat betapa memilukannya nasib dosen ASN di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi.
Sangat aneh jika ada dosen yang menyatakan bahwa tukin dosen ASN sifatnya inkonstitusional karena aturan yang mendasari untuk memproses pembayaran tukin sudah cukup jelas.
Ketidaktahuan dosen akan peraturan tukin tersebut mungkin menjadi alasan sepinya isu ini sebelumnya.
Hanya sejak digaungkan Kembali oleh Fatimah, isu ini Kembali bangkit dan memuncak di awal 2025.
Keramaian sosial media turut menstimulasi isu tukin ini di seluruh wilayah Indonesia. Nampaknya salah satu alasan viralnya isu tukin di sosial media adalah karena mulai bergabungnya para gen Z di dalam formasi dosen Indonesia.
Sebagaimana kita maklumi, gen Z adalah generasi yang melek teknologi dan sangat terkait erat dengan sosial media.
Bagi dosen Gen Z, sosial media bukan hanya platform teknologi tetapi juga ruang hidup yang menghubungkan mereka dengan dunia luas, mempengaruhi hampir semua aspek kehidupan mereka. Maka tak heran, isu tukin ini dengan segera menjadi viral di Indonesia.
Tantangan dan Pro Kontra Dalam Perjuangan Tukin Dosen
Upaya mendapatkan hak tukin dosen ASN ini bukan tanpa alasan yang jelas.
Kehadiran berbagai peraturan yang melegalisasi pembayaran tukin dosen ASN Kementerian Pendidikan tinggi sangat layak untuk diperjuangkan.
Dalam pergolakan ini, akhirnya dosen ASN seluruh perguruan tinggi negeri yang tergabung dalam Aliansi Dosen ASN Kemendiktisaintek (ADAKSI) melakukan aksi nasional di Jakarta pada 3 Februari 2025.
Aksi tersebut menghadirkan ratusan dosen dari Aceh hingga Papua yang berkumpul menyuarakan haknya.
Dalam aksi tersebut tersiar wacana akan ada aksi mogok mengajar jika tukin belum dicairkan. Ini cukup mengejutkan mengingat profesi ini merupakan profesi yang hampir belum pernah terdengar melakukan aksi semacam itu.
Amanah dan kewajiban Tri Dharma Perguruan Tinggi yang sudah menjadi jiwa dan warna kehidupan dosen menjadikan dosen nyaris manusia sempurna. Betapa tidak, dosen bertugas mengajar, mendidik, meneliti juga mengabdi kepada masyarakat.
Dapat dibayangkan bahwa jika sampai dosen melakukan aksi serentak, ini artinya memang sudah berada pada titik puncak yang tidak memiliki alternatif jalan lain.
Uniknya, dalam menyikapi gerakan aksi menuntut realisasi tukin ini para dosen sendiri belum seluruhnya berada dalam garis yang sama.
Dosen Indonesia masih belum satu suara dalam memperjuangkan tukin, padahal ini adalah hak yang layak untuk diperjuangkan.
Masih ditemukan riak-riak pro kontra dalam perjuangan ini. Hal tersebut dapat disebabkan oleh berbagai faktor.
Pertama bisa dilihat dari klasterisasi PTN yang sudah disinggung sebelumnya.
Dosen dari PTNBH bisa mendapatkan remunerasi dengan jumlah yang fantastis.
Dengan keistimewaan ini para dosen dari universitas besar PTNBH nampaknya tidak semua akan bersedia memperjuangkan tukin karena pada umumnya hidup mereka sudah sejahtera.
Walaupun menurut beberapa informasi, jumlah fantastis tersebut juga tidak merata dan hanya bisa dinikmati terutama oleh dosen yang memenuhi syarat tertentu.
Dosen-dosen yang sukar untuk memenuhi syarat tertentu tersebut nampaknya bersedia berada pada posisi berjuang untuk tukin.
Bagaimana dengan PTN BLU? Dosen dari klaster ini nampaknya tunjangan kesejahteraanya antara ada dan tiada.
Tidak sedikit yang mengaku bahwa PTN BLU masih non remun, artinya mereka bersatus BLU namun tidak mendapatkan hak remunerasi tersebut.
Bahkan, jika ada remun pun, jumlahnya minimalis dan tidak layak. Mungkin karena berbagai peraturan dan syarat yang juga tidak mudah untuk mengajukan remunerasi tersebut.
Akhirnya, dosen dari BLU juga kecewa dan pada umumnya bersedia ikut memperjuangkan tukin.
Selanjutnya adalah dosen dari PTN satker. Mereka inilah yang mungkin paling keras teriakannya untuk memperjuangkan tukin.
Bagi dosen satker, remunerasi sama sekali tidak dapat diimplementasikan. Rasionalnya, bagi dosen PTN satker tidak ada peluang mendapatkan remunerasi, mereka hanya bergantung pada penghasilan bulanan plus tunjangan.
Namun, toh masih banyak yang tidak ingin bersuara.
Mungkin ada banyak sebab dan polemik di dalam diri para dosen. Terdapat kekhawatiran bakal dicap sebagai dosen yang tidak pandai bersyukur adalah salah satu penyebab utama.
Mengapa dikatakan tidak pandai bersyukur? Karena dosen sudah memperoleh tunjangan sertifikasi/serdos.
Mungkin ada kekhawatiran akan dihujani komentar miring seperti “Apa tidak cukup gaji pokok dosen? Ditambah serdos plus tunjangan fungsional, plus uang makan?” atau komentar semacam “Pandai-pandailah mengatur keuangan dan pola hidup.”
Kedua, selain klasterisasi perguruan tinggi, jurang generasi antar dosen juga nampak menjadi penyebab perbedaan sikap tersebut. Dosen-dosen senior rata-rata berada pada rentang usia 40 s.d. 60-an.
Sementara dosen junior berada pada rentang usia sekitar 28 hingga 40-an . Jika dilihat dari usia, maka dosen senior tergolong generasi baby boomers, generasi X dan sebagian generasi Y (millennial). Sementara dosen junior sebagian besar berada pada generasi Z dan sebagian lainnya generasi Y (millennial).
Tentu saja para pejuang tukin ini berasal dari berbagai generasi, namun nampaknya dosen generasi Z dan generasi milenial mendominasi pergerakan ini. Dosen gen Z yang rata-rata merupakan dosen baru dengan status CPNS memandang beratnya upaya yang harus dilakukan dosen untuk meningkatkan kesejahteraan.
Rumitnya peraturan kenaikan pangkat dan fungsional hingga sukarnya persyaratan memperoleh serdos menjadi penyebab utama protes mereka.
Koalisi antar generasi ini akan menjadi sangat solid dan saling menguatkan jika didukung dengan keyakinan dan visi yang sama yaitu memperjuangkan hak yang sudah seharusnya didapatkan sejak bertahun-tahun yang lalu.
Ketiga, isu lainnya yang juga menarik adalah mengenai kemampuan bersyukur seorang dosen. Apakah dosen yang masuk ke dalam pergerakan perjuangan tukin ini layak digolongkan dosen yang tidak pandai bersyukur? Banyak yang beranggapan profesi dosen adalah profesi dengan gaji yang layak dan sesuai.
Gaji pokok dan tunjangan keluarga ditambah sertifikasi dosen, ditambah uang makan dianggap sudah cukup. Masyarakat tidak tahu bahwa serdos hanya bisa didapatkan melalui perjuangan yang tidak gampang.
Semakin ke sini persayaratannya semakin dipersulit.
Syarat waktu kerja sebagai dosen, tes TKDA, tes TOEFL / IELTS dan berbagai syarat lainnya yang tidak hanya membutuhkan waktu dan energi, tapi juga perlu menyiapkan dana yang tidak sedikit.
Jika melihat gaji para dosen baru, terlalu berat perjuangan untuk mendapatkan serdos ini.
Lalu bagaimana dengan dosen senior? Setali tiga uang, para dosen senior yang sudah lebih dahulu mendapatkan serdos dengan syarat yang relatif lebih mudah ternyata mempunyai kegalauan yang sama. Serdos adalah tunjangan bersyarat.
Agar tunjangan profesi (:serdos) tersebut bisa terus sustain, dosen harus mampu mempertahankan kinerjanya sesuai peraturan yang berlaku. Peraturan tersebut begitu mencekik dengan nilai tuntutan yang selangit. Publikasi di berbagai jurnal nasional dan internasional bereputasi adalah keharusan.
Sementara, biaya publikasi internasional tersebut nilainya bukan main-main bisa mencapai hingga belasan dan puluhan juta rupiah. Tentu saja ada jurnal internasional bereputasi yang free, atau dengan biaya lebih rendah, namun kompetisi untuk terbit di jurnal ini juga sangat tinggi.
Pada intinya beban dosen Indonesia sangatlah berat.
Tri Dharma dan Beban Kerja Dosen: Antara Kewajiban dan Tuntutan Kesejahteraan
Tri Darma Pendidikan di Indonesia nampak hanya menjadi sekedar simbol untuk mencapai target kinerja.
Target yang dikejar demi segepok uang serdos yang nilainya jauh di bawah nilai tukin. Tidak heran jika kemudian muncul kecemburuan sosial terjadap ASN lain yang sudah menerima tukin tanpa harus bersusah payah seperti dosen dalam hal serdos dan tunjangan fungsionalnya.
Selain jurang yang dalam untuk memenuhi persyaratan perolehan antara serdos dan tukin, besaran nilainya untuk jenjang jabatan yang sama juga sangat jauh berbeda. Satu contoh saja, untuk jabatan Asisten Ahli/AA (kelas jabatan 9), Tukin yang dijanjikan oleh Kepmendikbud Ristek No.447/P/2024 adalah sebesar Rp5.079.200,00.
Sementara nilai serdos hanya sebesar gaji pokok pegawai dengan jabatan asisten ahli tersebut, taruh kata dosen ini berada pada pangkat III b dengan masa kerja 0 tahun, maka nilai serdosnya sama dengan gapoknya yaitu sebesar kotor Rp2.903.000,00.
Dari sini bisa terlihat jelas jurang perbedaan Take Home Pay (THP) yaitu sekitar Rp7.900.000,00 bagi dosen dengan tukin dan hanya sekitar Rp5.800.000,00 bagi dosen dengan serdos.
Kesenjangan ini terus berlaku untuk setiap jenjang jabatan dosen sejak Asisten Ahli (AA) hingga Guru Besar (GB).
Padahal bagi dosen baru, untuk mendapatkan kesempatan berkompetisi memperoleh serdos saja butuh waktu tunggu hingga minimal 2 tahun, belum lagi batasan kuota dan waktu tunggu di Kementerian.
Kondisi lainnya yang cukup miris adalah beratnya beban yang harus ditanggung seorang dosen yang sedang Tugas Belajar (TUBEL). Saat seorang dosen sudah menyandang status Tubel maka dengan segera berbagai kewajiban seorang mahasiswa Tubel melekat padanya. Bersamaan dengan itu, berbagai hak yang sebelumnya dimiliki juga terhapus.
Peraturan menyatakan bahwa tunjangan sertifikasi dosen (SERDOS) dihentikan sejak 6 bulan setelah memulai masa tugas belajar. Sementara itu Permen Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi telah menghapus Permen Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional.
Perbahan Permen tersebut membawa akibat yaitu dihapuskannya hak tunjangan tugas belajar bagi dosen tubel semenjak tahun 2022.
Namun, Permen No.27, tahun 2022 tersebut menyatakan bahwa dosen dengan status tubel masih berhak mendapatkan tukin.
Penghentian serdos dan penghentian tunjangan fungsional tersebut sangat mempengaruhi well being dosen yang sedang menjalani tugas belajar.
Dengan adanya peraturan ini, maka sangat wajar jika dosen memperjuangkan hak tukinnya.
Mencari Keadilan untuk Dosen: Lebih dari Sekadar Tunjangan
Regulasi tentang tunjangan kinerja (tukin) dosen adalah hak yang sepatutnya segera diimplementasikan.
Perjuangan dosen untuk mendapatkan tukin tidak hanya sekedar masalah finansial, tetapi juga penghargaan terhadap kontribusi signifikan dosen dalam membentuk generasi yang akan datang.
Perbedaan pendapat di antara dosen dari berbagai generasi dan efek dari klasterisasi universitas menunjukkan bahwa menciptakan gerakan kolektif yang efektif adalah sesuatu yang kompleks.
Keberhasilan dalam perjuangan ini memerlukan persatuan suara yang bisa mengatasi perbedaan generasi dan struktur organisasi.
Sebagai bagian dari komunitas intelektual bangsa, dosen memiliki kewajiban moral untuk tidak hanya berjuang demi kesejahteraan mereka sendiri, tetapi juga untuk mendukung keadilan dalam skala yang lebih besar.
Dengan adanya komitmen dan solidaritas, diharapkan masalah ini bisa menjadi titik tolak untuk reformasi yang lebih adil dan terhormat dalam pendidikan tinggi Indonesia.
[oleh Andriani dan Nailiya Nikmah*]